CARAPANDANG - oleh Mujamin Jassin (Pemerhati Sosial Politik)
Pada pidatonya yang menggelegar di acara musyawarah rakyat (MUSRA) tempo lalu. Bukan endorsement kandidasi terhadap orang-orang tertentu yang membikin yang lainnya cemburu. Setidak-tidaknya Presiden Jokowi telah memberikan gambaran terang, menjawab kegalauan publik tentang spesifikasi, kriteria-kriteria otentisitas siapa yang cocok, layak, dan punya kepatutan kepemimpinan nasional pada perhelatan politik Pilpres tahun 2024 mendatang.
Implisitnya kriteria kuat, berani dan bernyali, membuat memori kolektif saya menemukan batas untuk membereskan atau menghentikan tantangan perkembangan konsep ‘kepemimpinan politik’ yang selalu kabur, menjadi tidak jelas, kompleks dan mendua. Lantaran kontestasi politik yang terlalu menitikberatkan pada sindrom popular, pragmatisme finansial. Pertengkaran politik yang mengandalkan dahsyat menggemanya buaian, efek meluasnya politik polesan, serta keriuhan berprospek pada saling balapan memburu gelembung elektoral.
Kegamblangan penyebutan kriteria-kriteria, sebagai jembatan penyeberangan yang juga meringkas kerumitan atau perdebatan definisi normative soal gaya, tipe, dan pola kepemimpinan. Yang seolah-olah dikotomis seperti tidak saling mengisi misalkan dari yang gaya administrative, tipe tradisional komunalistik, cara populistis, kemudian menyoal kedisiplinan kepemimpinan militeristik yang menghendaki kepatuhan mutlak pada sistem.
Studi dari kriteria ini pula, kita perlu coba membaca dan memahami secara dalam kontekstualnya, memang sebaiknya begitu. Sebba bila mengadaptasi dari tuturan makrifat Buya Hamka, kira-kira begini, bahwa membaca dengan baik seperti memberi asupan makanan yang baik kepada sumsum rohani-jiwa. Termasuk juga menangkap kontekstual pilihan kata cawe-cawe sehingga tak dibuat jadi polemik.
Guru Besar Ilmu Linguistik Universitas Gadjah Mada, I Dewa Putu Wijana. Dikutip dari detikCom, Rabu, 31 Mei 2023. Dia mengatakan bahwa cawe-cawe yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, bermakna ikut serta menangani sesuatu. Menurutnya, umum penggunaannya di segala aktivitas, makna cawe-cawe itu netral.
Cawe-cawe yang harus dimaknai positif, upaya menciptakan demokrasi yang berkualitas, urus berdemokratisasi hingga terkonsolidasi. Karena demokrasi harus menemukan kesejatiannya yang berujung keniscayaan pada peningkatan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa serta menjamin hak kedaulatan politik rakyat berdasar UUD 1945 dan Pancasila.
Dalam artian cawe-cawe tidak dibaca secara tekstual sehingga membuat ilusi negatif kemana-mana, seperti misalkan cawe-cawe itu tidak netral dan akan melemahkan demokrasi. Padahal sebetulnya ingin membantu mempersenjatai rakyat diantaranya misalkan dengan modal kriteria-kriteria itu tadi, sehingga kita dapat mencapai nilai idealnya demokrasi.
Sebab lagipula, bagaimana mungkin kita menafikkan, liberalisasi demokrasi yang kekinian kian mempertontonkan Pemilu, Pilpres, Pileg maupun hingga skup terkecil Pilkades semacam sebuah pertarungan bebas. Nihil substansi, hampir-hampir saja tak menetes efek kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semaraknya hanya berfungsi sekedar sarana politik rutinitas musiman belaka, berdemokrasi yang merumitkan, masih saja banyak sisi-sisi gelapnya kendati wacana demokrasi telah cukup tua usianya.
Halaman : 1
Pada pidatonya yang menggelegar di acara musyawarah rakyat (MUSRA) tempo lalu. Bukan endorsement kandidasi terhadap orang-orang tertentu yang membikin yang lainnya cemburu. Setidak-tidaknya Presiden Jokowi telah memberikan gambaran terang, menjawab kegalauan publik tentang spesifikasi, kriteria-kriteria otentisitas siapa yang cocok, layak, dan punya kepatutan kepemimpinan nasional pada perhelatan politik Pilpres tahun 2024 mendatang.
Implisitnya kriteria kuat, berani dan bernyali, membuat memori kolektif saya menemukan batas untuk membereskan atau menghentikan tantangan perkembangan konsep ‘kepemimpinan politik’ yang selalu kabur, menjadi tidak jelas, kompleks dan mendua. Lantaran kontestasi politik yang terlalu menitikberatkan pada sindrom popular, pragmatisme finansial. Pertengkaran politik yang mengandalkan dahsyat menggemanya buaian, efek meluasnya politik polesan, serta keriuhan berprospek pada saling balapan memburu gelembung elektoral.
Kegamblangan penyebutan kriteria-kriteria, sebagai jembatan penyeberangan yang juga meringkas kerumitan atau perdebatan definisi normative soal gaya, tipe, dan pola kepemimpinan. Yang seolah-olah dikotomis seperti tidak saling mengisi misalkan dari yang gaya administrative, tipe tradisional komunalistik, cara populistis, kemudian menyoal kedisiplinan kepemimpinan militeristik yang menghendaki kepatuhan mutlak pada sistem.
Studi dari kriteria ini pula, kita perlu coba membaca dan memahami secara dalam kontekstualnya, memang sebaiknya begitu. Sebba bila mengadaptasi dari tuturan makrifat Buya Hamka, kira-kira begini, bahwa membaca dengan baik seperti memberi asupan makanan yang baik kepada sumsum rohani-jiwa. Termasuk juga menangkap kontekstual pilihan kata cawe-cawe sehingga tak dibuat jadi polemik.
Guru Besar Ilmu Linguistik Universitas Gadjah Mada, I Dewa Putu Wijana. Dikutip dari detikCom, Rabu, 31 Mei 2023. Dia mengatakan bahwa cawe-cawe yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, bermakna ikut serta menangani sesuatu. Menurutnya, umum penggunaannya di segala aktivitas, makna cawe-cawe itu netral.
Cawe-cawe yang harus dimaknai positif, upaya menciptakan demokrasi yang berkualitas, urus berdemokratisasi hingga terkonsolidasi. Karena demokrasi harus menemukan kesejatiannya yang berujung keniscayaan pada peningkatan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa serta menjamin hak kedaulatan politik rakyat berdasar UUD 1945 dan Pancasila.
Dalam artian cawe-cawe tidak dibaca secara tekstual sehingga membuat ilusi negatif kemana-mana, seperti misalkan cawe-cawe itu tidak netral dan akan melemahkan demokrasi. Padahal sebetulnya ingin membantu mempersenjatai rakyat diantaranya misalkan dengan modal kriteria-kriteria itu tadi, sehingga kita dapat mencapai nilai idealnya demokrasi.
Sebab lagipula, bagaimana mungkin kita menafikkan, liberalisasi demokrasi yang kekinian kian mempertontonkan Pemilu, Pilpres, Pileg maupun hingga skup terkecil Pilkades semacam sebuah pertarungan bebas. Nihil substansi, hampir-hampir saja tak menetes efek kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semaraknya hanya berfungsi sekedar sarana politik rutinitas musiman belaka, berdemokrasi yang merumitkan, masih saja banyak sisi-sisi gelapnya kendati wacana demokrasi telah cukup tua usianya.









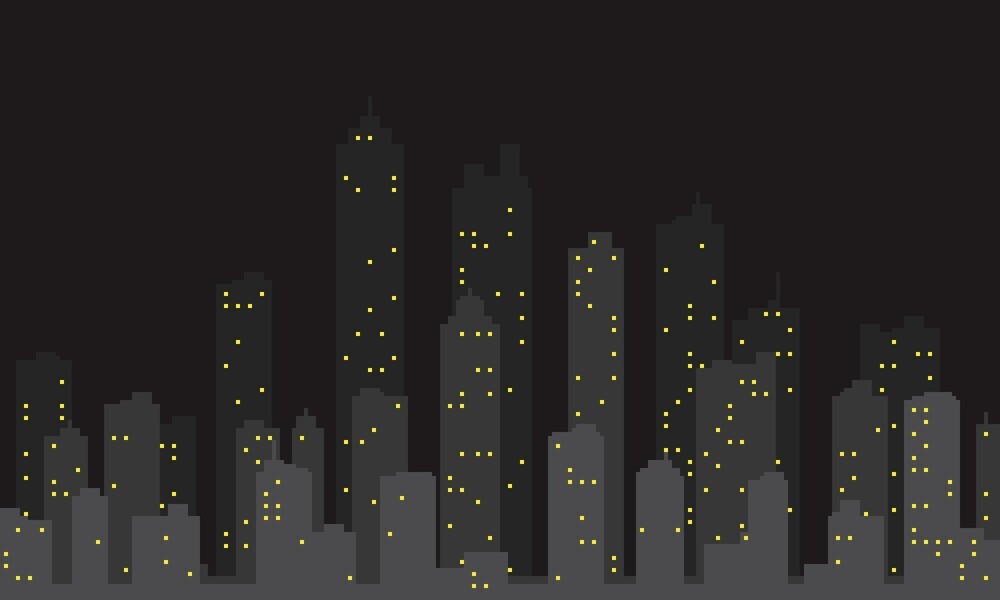


.jpg)








